Ibu Ku Seorang Pembohong
“Bu...apakah aku sudah boleh sekolah?”,
tanyaku pada ibu yang sedang memasak goreng ikan di dapur. Ibu tersenyum mengampiriku,
“umur kamu masih empat tahun nak, itu artinya belum cukup untuk bisa
bersekolah”, ibu membelai rambut ku. Tapi aku terus bersikeras ingin
bersekolah, aku bosan dirumah apalagi ketika itu rumah kami hanya berjarak lima
meter dari sekolah. “aku mau sekolah bu, kalau tidak boleh, aku mau ikut taman
kanak-kanak saja,” kerasku. Ibu ku begitu sabar, ia memberitahu ku bahwa taman
kanak-kanak hanya ada di ibukota kecamatan sedangkan kami berada satu jam dari
ibukota kecamatan, satu jam karena jalan yang begitu buruk pada waktu itu.
Hujan saja sedikit maka dijamin kendaraan akan susah payah memasuki desa kami.
Ibu ku adalah salah seorang dari tamatan
sekolah pendidikan guru atau SPG yang ketika itu mengabdi di sebuah sekolah
inpres. Jumlah ruangan kelas hanya empat ruangan saja, sedangkan jumlah guru
hanya ada tiga termasuk ibu, sedang satu orang lagi bolak-balik dari ibukota
kecamatan. Sekitar tahun 1994 aku dan ibu telah menginjakkan kaki di desa itu,
jauh dari keramaian dan hiruk pikuk kendaraan bermotor, yang ada hanya suara
jangkrik dan ayam jantan jika pagi menjelang. Kala itu desa kami belum dialiri
listrik, sehingga kami harus puas dengan lampu teplok, semua aktivitas malam
bergantung pada lampu teplok. Membaca buku, menulis, mengaji, semuanya
mengandalkan lampu teplok.
Setiap hari aku selalu meminta untuk
sekolah kepada ibu, kadang aku merengek tetapi ibu selalu tersenyum. Memang aku
dibawa setiap beliau mengajar di kelas tetapi aku ingin memakai seragam merah
putih, dasi dan topi warna merah. Aku ingin pandai membaca, menulis dan
berhitung.
Hari itu adalah hari pasar di ibukota
kecamatan, tepatnya setiap hari selasa maka ratusan mungkin ribuan orang datang
berbondong-bondong pergi ke pasar kecamatan. Aku dulu suka pergi ke pasar,
merasakan sensasi keramaian dan hiruk pikuk pasar, sekarang tidak lagi, aku
benci dan tidak suka dengan pasar. Hanya ada satu kendaraan dari desa kami berupa
mobil jenis pick up yang diberi tempat duduk dua baris berhadap-hadapan, dengan
itu lah masyarakat desa pergi ke pasar setiap hari selasa. Jika kita tidak
berhati-hati maka jangan heran kepala akan terkena atap mobil pick up karena
lobang-lobang sebesar kolam ikan yang akan dilalui. Tidak jarang juga kita
melihat kelompok-kelompok orang yang rela berjalan kaki dari pagi untuk
mencapai pasar, bisa dibayangkan bahwa dengan menggunakan kendaraan bermotor
sudah menghabiskan waktu cukup lama, tapi mereka tetap semangat berjalan kaki.
Biasanya pasangan muda-mudi. Selepas mengajar ibu memberitahu ku bahwa kami
akan pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan makan selama satu minggu. Sudah aku
bilang tadi di atas bahwa aku senang jika ibu mengajak ke pasar, kami naik
mobil pick up bersama dengan orang desa lain yang kebanyakan adalah ibu-ibu.
Beberapa dari mereka ada yang juga memeluk anaknya, sedangkan beberapa lelaki
memilih berdiri menggelantung dibelakang mobil. Ramai sekali di dalam mobil,
penuh sesak.
Kira-kira satu jam kemudian kami sampai di
pasar, semua penumpang turun termasuk aku dan ibu ku. Kami berjalan kaki
beberapa meter untuk masuk ke dalam pasar, ibu mengajak ku menyantap sate
terlebih dahulu karena memang kami belum makan siang. Semua kebutuhan yang kami
perlukan disediakan oleh pasar, minyak goreng, beras, lauk pauk, ikan asin,
sayur, pakaian, semuanya ada. Karena masih kental dengan konsep tradisional
maka suara tawar menawar menambah suasana riuh pasar. Ibu juga tergolong kepada
penawar ulung, ia selalu berpesan kepadaku bahwa hati-hati dalam membeli
sesuatu. “kalau tidak penting dan mendesak kita tidak usah beli dulu,” beliau
selalu mengingatkan aku. Tidak butuh waktu berapa lama, keranjang belanjaan ibu
sudah penuh berisi berbagai macam barang. Tiba-tiba ibu menarik tangan ku,
“sini nak, mau baju yang mana”, ibu memberikan aku beberapa pilihan baju
sekolah. Aku kaget, kemarin ibu masih belum mengijinkan aku untuk sekolah.
“pilih dulu, coba kamu pake dulu”, ibu menyodorkan satu stel baju merah putih.
Pas, dan ibu kembali melakukan tawar menawar dengan penjual baju, kali ini
cukup alot sehingga aku pun cemas apabila ibu tidak sepakat dengan harga yang
ditetapkan penjual. Cukup lama aku menunggu, akhirnya bungkusan plastik berisi
seragam sekolah itu aku genggam. Jantung ku berdebar, aku masih empat tahun,
“ah yang jelas aku ingin sekolah”, gumamku.
Kami kembali ke desa dengan menumpang
mobil yang sama, kali ini lebih sesak karena ibu-ibu pulang dengan membawa
keranjang penuh terisi, bahkan atap mobil pun tak luput dari tumpukan barang,
umumnya kelapa. Setibanya dirumah aku langsung membuka bungkusan plastik hitam,
kembali aku kenakan sembari aku berlagak di depan kaca lemari. Ayah ku hanya tersenyum
melihat tingkah laku ku, maklum beliau tidak terlalu banyak bicara soal
pendidikan. Tidak sabar rasanya menunggu hari esok, mengenakan seragam dan
belajar bersama ibu.
Pagi-pagi sekali ibu membangunkan aku,
“mau sekolah kan? Ayo bangun lagi nanti terlambat,” ibu menyentuh pipiku dengan
tangannya, dingin. Cara ibu membangunkan dengan menyentuh pipih masih aku
rasakan hingga sekolah menegah atas, selalu dingin karena ibu baru saja selesai
mandi. Aku meloncat dari tempat tidur, bergegas mandi dan mengenakan seragam
baru yang dibelikan ibu kemarin, aroma khas pakaian baru. Tidak lupa aku
mengenakan sepatu yang dibelikan oleh ibu waktu lebaran tahun kemarin, “sudah
rapi anak ibu, ayok makan dulu lepas itu kita berangkat”, ibu menyuapi aku nasi
dengan telur mata sapi. Aku masih empat tahun dan sekarang aku berada di dalam
ruangan kelas dengan anak-anak berumur enam tahun, sama hal nya dengan mereka
cuma saja aku belum terdaftar sebagai siswa resmi. Hanya mengikuti yang
dijelaskan oleh ibu di depan kelas, sesekali ibu datang ke mejaku yang berada
persis di depan mejanya, ia membetulkan caraku memegang pensil. Susah sekali
memang belajar menulis untuk pertama kalinya, begitulah seterusnya hingga
beberapa bulan kemudian aku sudah bisa menulis dan membaca dengan lancar.
Atas prestasiku yang bisa membaca diumur
empat tahun ibu sering membanggakan aku di depan ibu-ibu yang lain, “Diko umur
empat tahun sudah bisa membaca dan menulis,” begitu ibu selalu bilang.
Ibu tidak hanya terampil mengajar di
kelas, bagiku ia adalah sosok yang serba bisa. Suatu kali kami tidak memiliki
lauk untuk dimasak, ibu langsung mengajak aku dan ayah pergi ke sungai
menangkap udang dan ikan kecil yang nantinya bisa kami santap. Waktu itu aku
masih belum bisa berenang, jadi aku selalu berpegangan pada tangan ayah. Kami
bertiga menuju hilir sungai untuk mencari udang dan ikan kecil, hingga sore
hari setengah kantong yang terbuat dari anyaman daun pandan sudah terisi udang
dan beberapa ikan kecil. Tidak hanya kami, kebanyakan dari warga desa masih
memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan. Walaupun ibu seorang guru, tapi
pada masa itu menjadi guru adalah pekerjaan yang menyakitkan jika diukur dari
segi kesejahteraan.
Sesekali ayah mengajak aku pergi ke hutan
untuk menembak burung sebagai lauk makan malam kami, “Ko, kemaren ayah lihat
ada pohon yang berbuah, sepertinya banyak burung disana,” ia mengajakku.
Terkadang kami hanya pergi berdua ke dalam hutan, sering juga bersama beberapa
orang teman ayah. Aku selalu bertugas sebagai tukang kumpul burung yang telah
terkena tembakan, kadang kasihan tetapi kami butuh makan. Ayah rela
bergelantungan di atas dahan kayu, mengendap diantara semak belukar dan
menunggu dengan sabar hingga burung datang menghampiri batang kayu yang
ditargetkan. Sama dengan kebanyakan anak lainnya, aku juga sering menghabiskan
waktu bersama dengan teman-teman sebaya, belajar menjerat burung, main
perosotan tanah, membuat miniatur kapal lalu kami lombakan di sungai, berbagai
macam permainan yang semuanya kami dapatkan secara gratis.
Tidak terasa dua tahun sudah kami tinggal
di desa, dan aku tidak pernah libur sekolah hingga akhirnya surat keputusan ibu
keluar, beliau ditugaskan untuk mengajar di sekolah dasar negeri ibukota
kecamatan. Aku senang, sekarang aku sudah berumur enam tahun artinya aku bisa
menjadi seorang siswa resmi. “besok mulai sekolah lagi, masuk kelas satu jangan
malas-malas kayak dulu lagi,” memang aku agak malas waktu masih di desa.
Beruntungnya aku, adalah ketika proses belajar dan mengajar terjadi aku hampir
paham semua yang diajarkan oleh guru, kali ini bukan ibu lagi yang jadi guru.
Aku membaca dengan lancar sehingga teman-teman yang lain iri kepada ku. “anak
guru panteslah bisa langsung,” begitu cemoohan yang selalu aku terima. Walaupun
begitu aku tidak pernah mendapatkan ranking satu, Ifanna selalu ranking satu
dan aku rangking dua begitu terus hingga aku menamatkan sekolah dasar.
Sekolah menengah pertama adalah masa-masa
sulit, karena aku mendapatkan lebih banyak saingan murid-murid yang pintar dan
aku adalah orang yang benci dengan matematika. Kehidupan kami semakin sulit,
karena tidak hanya aku tetapi dua orang adek ku harus bersekolah, sedangkan
gaji ibu dengan penghasilan ayah yang tidak menentu mulai menimbulkan masalah
bagi kami. Maklum ayah tidak memiliki pekerjaan tetap, walaupun begitu beliau
juga bisa menghidupi kami secukupnya. Kadang beliau berjualan rotan, kayu,
kadang buah manggis, kadang sarang walet apapun itu yang menghasilkan uang.
Suatu sore aku menghampiri ibu yang tengah
menggoreng tempe di dapur, wajahnya terlihat sedih, seperti ada sesuatu yang
merasuki fikirannya. “kenapa bu?, ada yang salah?”, tanya ku. Ibu menghampiri
aku, memeluk ku tidak seperti biasanya, ia menangis, “belajar yang rajin ya
nak, pokoknya anak ibu harus lebih baik dari ibu dan ayah, ibu sudah menabung
untuk kuliah kamu nanti”, ibu terisak. Aku bingung, air mataku ikut menetes,
“iya bu aku janji bakalan membuat ibu bahagia kelak,” aku menahan tangis agar
tidak terisak. Waktu itu aku masih kelas dua sekolah menengah pertama. Berbeda
dengan teman yang lain aku bahkan tidak punya uang jajan berlebih untuk aku
tabung, tidak jarang juga aku tidak jajan disekolah cuma cukup untuk ongkos
naik ojek ke sekolah. Aku tidak sedih, tidak takut dan juga tidak gentar
menghadapi kenyataan ditengah orang lain mampu hidup berkecukupan. Buktinya
prestasiku juga tidak terlalu buruk di sekolah, selalu berada dalam lingkaran
lima besar, masih tidak bisa menjadi ranking satu. Aku juga terpilih menjadi
ketua OSIS sewaktu SMP, yang aku sendiri tidak paham kenapa aku bisa menjadi
ketua OSIS.
Masa SMP berlalu, sekarang masa yang
orang-orang paling indah, masa SMA. Kami masih belum bisa keluar dari masa-masa
sulit, tetapi ibu selalu berusaha memberiku semangat, kata-kata tabungan
rahasia selalu ia bisikkan ke telinga ku. Beberapa minggu sebelum ujian
nasional aku berbicara pada ibu, “bu nanti aku mau melanjutkan kuliah,
bagaimana menurut ibu?”, aku sedang mengerjakan PR di meja belajar. “tenang nak..sekarang
belajar dulu yang rajin, soal kuliah ibu sudah ada tabungan cukup hingga kamu
tamat kuliah”, ibu menenangkan aku. Aku mendapatkan nilai bagus ketika ujian
nasional di SMA kecuali nilai matematika, lagi-lagi matematika. Tidak ada hal
yang paling aku ingin waktu itu selain melanjutkan pendidikan ke jenjang yang
lebih tingggi, aku ingin kuliah seperti kebanyakan anak lain. Keinginan yang
tinggi aku padukan dengan usaha dan doa, aku lulus seleksi dan diterima di
perguruan tinggi ternama.
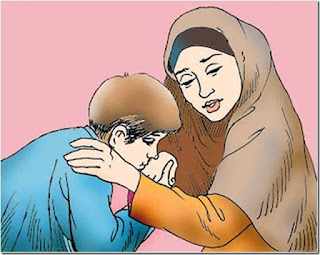 |
| *ist |
Girang bukan kepalang, aku menagih janji
ibu untuk membayar biaya awal kuliah. “bu aku lulus, besok harus daftar ulang,
syarat dan biayanya cukup banyak,” aku menyampaikan berita gembira itu. Ibu
tersenyum, senang jelas nampak dari raut wajahnya, namun kerut di keningnya
seperti ada hal buruk yang sedang ia khawatirkan. “besok ibu temani daftar
ulang, kita berangkat pagi-pagi esok,” ibu menenangkan aku.
Malam harinya aku mempersiapkan beberapa
berkas yang akan aku bawa besok hari, ketika melewati kamar ibu, aku mendengar
nya sedang bercakap-cakap dengan ayah. “besok Diko mau daftar ulang, dia begitu
bersemangat, sedang kita tidak punya uang, bagaimana yah?”, aku mengentikan
langkah. Mereka jelas tidak mendengarkan derap langkah ku, “coba nanti dulu aku
akan cari pinjaman buat dia besok”, timpal ayah. Mendengar ucapan ibu aku
tertunduk lesu, aku mengerti selama ini dari kecil ibu telah membohongi aku, ia
berpura-pura memiliki tabungan untuk kuliah ku, agar aku tetap semangat sekolah.
Air mataku menetes, sedang mereka masih berdebat soal uang pendaftaran esok
hari, aku pun berlalu kembali menyiapkan berkas, mengigit bibirku.
Dalam benaku masih berkecamuk, di satu
sisi aku ingin sekali kuliah mengecap pendidikan tinggi, sedangkan sisi lain
kedua orang tua ku sedang terseok mencukupi kebutuhan kuliah ku. Esok paginya
ibu membangunkan aku dengan tangan nya yang dingin menempel di pipi ku, “bangun
nak,.. kan mau daftar ulang,” ia tersenyum. Sekarang aku tahu semua kebohongan
ibu selama ini, aku sadar ia berbohong untuk kebaikan dan aku tidak akan
memberikan celah kegagalan. Kami berangkat, aku serasa kembali menjadi anak umur
empat tahun. Ibu....terima kasih atas kebohongan yang pintar selama ini.
*nanda bismar, 18.10.2015

Merinding bacanya bgg... So gooddd.. :'))))
ReplyDelete:')
ReplyDeleteTerima kasih :)
ReplyDeleteIni yang paling ara suka jadinya bg :')
ReplyDeleteterima kasih ara...
Delete